Dalam derasnya berita buruk, konflik, dan polarisasi dunia hari ini, Humankind: A Hopeful History karya Rutger Bregman hadir sebagai sebuah oase yang meneguhkan keyakinan paling sederhana namun paling sulit dipercaya: bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang baik.
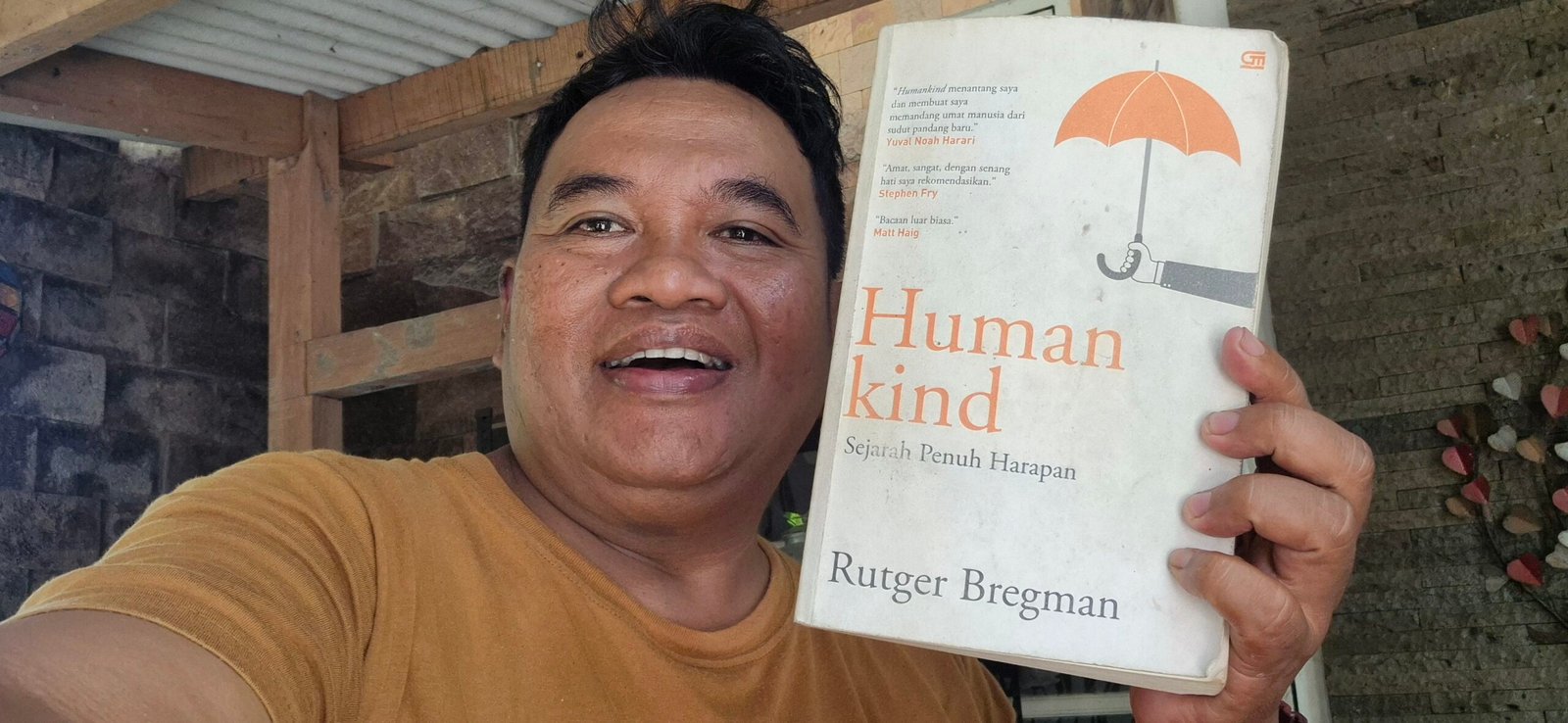
Klaim ini mungkin terdengar naif, tetapi Bregman—seorang sejarawan muda asal Belanda yang terkenal lewat gagasan progresifnya tentang universal basic income, keadilan sosial, hingga kritik tajamnya terhadap para miliarder di forum Davos—mengemasnya dengan bukti sejarah, psikologi, dan antropologi yang begitu kaya sehingga kita tak bisa begitu saja menolaknya.
Sejak halaman-halaman awal, Bregman mengguncang banyak asumsi yang kita anggap kebenaran umum.
Salah satu bagian paling memikat adalah kisah nyata enam remaja Tonga yang terdampar selama lebih dari setahun di sebuah pulau terpencil pada 1960-an.
Berbeda total dengan kegilaan dan kekacauan dalam novel Lord of the Flies, para remaja ini justru membangun komunitas kecil yang harmonis, saling merawat, dan menetapkan disiplin bersama.
Fakta ini terasa seperti pukulan telak kepada narasi gelap yang sering kita percayai tentang apa yang terjadi ketika “peradaban runtuh”—bahwa kekacauan adalah natur manusia. Dalam realitasnya, manusia sering memilih jalan yang lebih tenang dan kooperatif.
Bregman kemudian membawa pembaca menelusuri kembali berbagai eksperimen psikologi klasik yang selama puluhan tahun membentuk persepsi publik tentang sifat manusia, seperti Stanford Prison Experiment dan eksperimen kepatuhan Milgram. Dengan paparan dokumentasi dan wawancara terkini, ia menunjukkan bagaimana banyak eksperimen ini ternyata penuh cacat metodologis, dilebih-lebihkan, atau dipandu terlalu jauh oleh bias penelitinya sendiri.
Menyadari bahwa fondasi yang selama ini kita pakai untuk memahami sifat manusia ternyata rapuh adalah pengalaman membaca yang mengejutkan sekaligus membebaskan: mungkin kita lebih baik dari yang kita kira.
Pada level sejarah panjang, Bregman menunjukkan bahwa masyarakat pemburu-peramu yang hidup jauh sebelum lahirnya negara modern justru memiliki pola hidup yang egaliter, berbagi sumber daya, dan cenderung kooperatif.
Sifat ramah dan kecenderungan untuk bekerja sama ternyata bukan hasil peradaban modern, melainkan warisan purba yang mengalir dalam gen kita.
Bahkan dari sisi biologis, ia menunjukkan bahwa selama ribuan tahun, wajah manusia perlahan mengecil dan membulat—indikasi proses self-domestication—yang dalam bahasa sederhana berarti bahwa kita telah berevolusi menjadi makhluk yang semakin jinak, sosial, dan toleran.
Kekuatan terbesar buku ini adalah bagaimana Bregman menggabungkan temuan ilmiah dengan gaya bercerita yang hidup, tajam, namun tetap humanis. Ia menulis bukan sekadar untuk mematahkan sinisme, tetapi untuk membangun kembali keyakinan rasional bahwa kepercayaan antarmanusia adalah fondasi paling efektif dalam membangun masyarakat.
Di tengah dunia yang dipenuhi rasa takut, polarisasi, dan kecenderungan melihat manusia sebagai ancaman, Humankind menjadi pengingat bahwa kerjasama, empati, dan saling percaya adalah kekuatan evolusioner yang memungkinkan spesies kita bertahan.
Buku ini bukan sekadar menghibur dengan optimisme; ia menantang kita untuk menata ulang cara melihat manusia—termasuk diri sendiri. Bregman tidak meminta kita memungkiri sisi gelap manusia, tetapi mengajak melihat bahwa di balik semua itu, kita memiliki potensi kebaikan yang jauh lebih besar daripada yang selama ini diceritakan oleh sejarah versi paling gelap.
Humankind adalah buku yang layak dibaca, direnungkan, dan dijadikan dasar harapan baru, terutama ketika dunia terasa penuh kekacauan dan ketidakpastian ini.

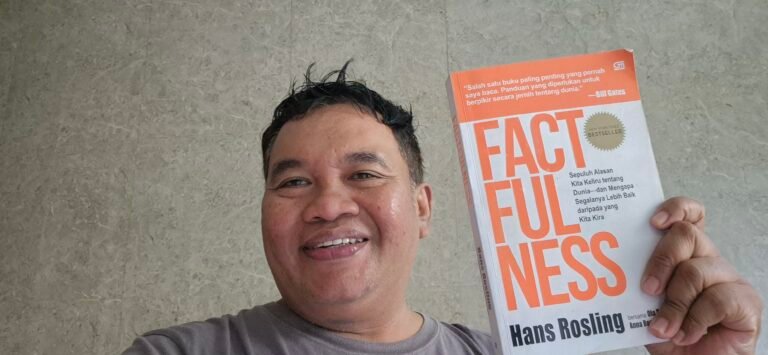
Leave a Comment